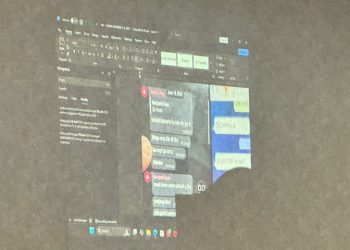Rencana strategis pemerintah untuk mengintegrasikan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas dalam program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Februari 2026 kini berada di bawah sorotan tajam publik dan pengamat kebijakan. Langkah ini, meski dipandang sebagai upaya penguatan operasional program nasional, dinilai memicu gelombang ketidakadilan yang substansial di tengah carut-marutnya penataan tenaga non-ASN di Indonesia. Kritik keras muncul karena kebijakan ini dianggap memberikan “karpet merah” bagi personel SPPG untuk meraih status aparatur sipil negara dengan mekanisme yang relatif instan, sementara di sisi lain, ratusan ribu guru honorer dan tenaga kesehatan yang telah mendedikasikan hidupnya selama belasan hingga puluhan tahun masih terjebak dalam ketidakpastian administratif dan kesejahteraan yang minim. Ketimpangan ini bukan sekadar masalah birokrasi, melainkan cerminan dari prioritas anggaran yang dianggap lebih condong pada program-program populis yang bersifat konsumtif dibandingkan penguatan fondasi pelayanan dasar negara yang krusial bagi keberlanjutan sumber daya manusia di masa depan.
Muhammad Eko Atmojo, seorang Peneliti Kebijakan Publik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), memberikan analisis mendalam mengenai potensi keretakan sosial dan kegagalan tata kelola jika rencana ini dipaksakan tanpa evaluasi menyeluruh. Menurutnya, pemerintah harus melihat secara jernih bahwa mekanisme pengangkatan pegawai SPPG menjadi PPPK menciptakan preseden buruk dalam sistem meritokrasi di lingkungan birokrasi Indonesia. Ia menyoroti adanya disparitas perlakuan yang sangat kontras antara proses rekrutmen pegawai SPPG dengan jalur seleksi yang sangat kompetitif dan melelahkan yang harus dilalui oleh tenaga pendidik serta tenaga kesehatan selama ini. Dalam pandangan Eko, kebijakan ini perlu ditinjau ulang secara fundamental, bukan hanya karena urgensi programnya, tetapi karena metode pengangkatannya yang terkesan mengabaikan prinsip kesetaraan peluang bagi seluruh warga negara yang ingin mengabdi pada negara melalui jalur PPPK.
Kontradiksi Mekanisme Seleksi dan Ancaman Terhadap Prinsip Keadilan Birokrasi
Persoalan utama yang menjadi titik didih kritik ini adalah mekanisme pengangkatan yang dianggap tidak setara dan cenderung eksklusif bagi kelompok tertentu. Selama ini, para guru honorer dan tenaga kesehatan harus melewati berbagai tahapan seleksi yang sangat ketat, mulai dari seleksi administrasi yang rigid, tes kompetensi dasar, hingga evaluasi kinerja berlapis yang seringkali memakan waktu bertahun-tahun tanpa jaminan kelulusan. Namun, dalam kasus pegawai SPPG, terdapat indikasi kuat bahwa pengangkatan mereka akan dilakukan secara otomatis atau melalui skema khusus yang jauh lebih mudah dibandingkan prosedur standar ASN. Eko menegaskan bahwa di Yogyakarta pada Jumat, 23 Januari 2026, ia melihat fenomena ini sebagai bentuk pengabaian terhadap rasa keadilan kolektif. Jika pemerintah terus melanjutkan skema pengangkatan otomatis ini, maka legitimasi sistem seleksi PPPK yang selama ini dibangun dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas akan terdegradasi secara signifikan di mata masyarakat luas.
Lebih jauh lagi, status asli dari para pegawai SPPG ini menambah kompleksitas masalah hukum dan etika kebijakan publik. Secara administratif, banyak dari personel SPPG merupakan pekerja yang berada di bawah naungan perusahaan swasta atau mitra pihak ketiga yang bekerja sama dengan pemerintah dalam pengadaan layanan gizi. Mengonversi status pekerja swasta menjadi pegawai negara melalui skema PPPK dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan langkah yang sangat tidak lazim dalam praktik tata kelola pemerintahan yang sehat. Penggunaan dana publik untuk menggaji tenaga kerja yang secara fungsional berasal dari entitas bisnis atau kemitraan sektoral dianggap sebagai bentuk inefisiensi anggaran dan potensi pelanggaran terhadap struktur penggajian negara yang seharusnya diprioritaskan untuk fungsi-fungsi pelayanan publik yang bersifat permanen dan fundamental, seperti pendidikan dan kesehatan dasar.
Dampak Jangka Panjang: Erosi Kepercayaan Publik dan Penurunan Motivasi Sektor Krusial
Implikasi dari kebijakan yang dianggap diskriminatif ini diprediksi akan memperlebar jurang ketimpangan sektoral yang sudah lama terjadi di Indonesia. Para pejuang di sektor pelayanan dasar, khususnya guru dan perawat di daerah terpencil, seringkali merasa dianaktirikan karena pemerintah dianggap lebih memprioritaskan kebijakan yang memberikan dampak visual dan instan secara politik, seperti program Makan Bergizi Gratis, daripada memperbaiki sistem penggajian guru honorer yang masih jauh di bawah standar hidup layak. Eko memperingatkan bahwa ketimpangan ini bukan masalah sepele; pendidikan dan kesehatan adalah dua pilar utama pembangunan kualitas sumber daya manusia serta ketahanan nasional. Jika sektor-sektor ini terus diabaikan demi memuluskan program sektoral baru, maka fondasi kemajuan bangsa dalam jangka panjang akan terancam rapuh akibat rendahnya motivasi para penggerak utamanya.
Dampak psikologis dan sosiologis dari kebijakan ini jika diteruskan tidak hanya akan berhenti pada menurunnya moralitas kerja para guru honorer yang merasa dikhianati oleh sistem. Lebih berbahaya lagi, kebijakan ini berpotensi memicu munculnya ketidakpercayaan publik secara masif atau distrust terhadap kredibilitas pemerintah dalam mengelola keadilan sosial. Eko menekankan bahwa ketika rasa keadilan diabaikan demi kepentingan pragmatis program tertentu, maka integritas pemerintah dalam menjalankan sistem demokrasi dan supremasi hukum akan ikut terancam. Masyarakat akan melihat bahwa status kepegawaian negara bisa didapatkan melalui jalur pintas asalkan berada di bawah program yang sedang menjadi prioritas politik, bukan berdasarkan kompetensi dan pengabdian yang telah teruji dalam waktu lama.
Rekomendasi Strategis: Memisahkan Program Nasional dari Beban Birokrasi ASN
Sebagai solusi konkret atas polemik ini, Eko menyarankan agar pemerintah tetap menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai target tanpa harus melakukan intervensi terhadap status kepegawaian para pekerjanya menjadi ASN atau PPPK. Ia merekomendasikan sebuah model pengelolaan yang lebih profesional dan akuntabel, di mana tanggung jawab penggajian dan manajemen sumber daya manusia tetap berada pada lembaga pelaksana atau mitra swasta yang ditunjuk. Dengan skema ini, negara tetap bisa menjamin keberlangsungan program pemenuhan gizi tanpa harus menambah beban belanja pegawai tetap di APBN yang sifatnya jangka panjang dan kaku. Hal ini juga akan memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengalokasikan fokus serta anggaran yang lebih besar guna menyejahterakan guru dan tenaga kesehatan yang selama ini menjadi ujung tombak dalam menjaga kualitas generasi bangsa.
Pada akhirnya, kebijakan publik yang efektif haruslah dibangun di atas landasan keadilan dan keberlanjutan, bukan sekadar respons cepat terhadap kebutuhan operasional sesaat. Pemerintah dituntut untuk bersikap adil dengan menuntaskan terlebih dahulu janji-janji kepada para tenaga honorer yang telah lama mengabdi sebelum membuka pintu istimewa bagi kelompok baru. Transparansi dalam proses rekrutmen dan kejelasan status hukum bagi setiap pekerja yang dibiayai oleh negara adalah kunci untuk menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Tanpa adanya koreksi terhadap rencana pengangkatan pegawai SPPG ini, pemerintah berisiko menciptakan bom waktu birokrasi yang dapat merusak tatanan manajemen ASN yang sedang berusaha diperbaiki melalui berbagai reformasi birokrasi dalam beberapa tahun terakhir.
Pilihan Editor: Kisah Guru Pendidikan Pancasila Digaji Rp 300 Ribu Sebulan