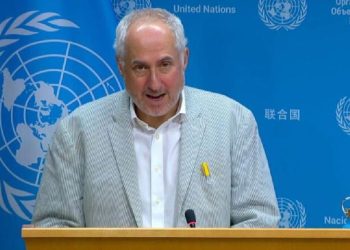Keputusan monumental pemerintah Indonesia untuk meresmikan keanggotaannya dalam sebuah forum internasional yang digagas oleh Amerika Serikat (AS), yang dikenal sebagai Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP), telah memicu gelombang sorotan tajam dan analisis mendalam dari berbagai kalangan, terutama di lingkungan akademisi. Langkah strategis ini, yang diumumkan secara resmi pada 22 Januari 2026, dipertanyakan bukan hanya dari perspektif diplomasi semata, tetapi juga dikhawatirkan dapat berujung pada delegasi kedaulatan dan mengikis prinsip fundamental politik luar negeri Indonesia yang telah mengakar kuat: bebas aktif. Bagaimana Indonesia menavigasi perairan diplomasi global yang kompleks ini, dan apa implikasi jangka panjang dari keputusan bersejarah ini terhadap posisinya di pentas dunia? Pertanyaan-pertanyaan krusial ini menjadi inti dari diskusi yang berkembang pesat.
Di tengah riuh rendahnya perdebatan publik, suara kritis datang dari Universitas Palangka Raya (UPR), khususnya dari Suherman, seorang akademisi yang mendalami Ekonomi Pembangunan. Ia secara tegas mengemukakan pandangannya bahwa bergabungnya Indonesia ke dalam Dewan Perdamaian bentukan AS membawa risiko yang signifikan terhadap posisi tawar negara di kancah internasional. Menurut Suherman, identitas Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip Non-Blok, yang selama ini telah berhasil memposisikan diri sebagai “jembatan” perdamaian dan mediator dalam berbagai konflik global, kini terancam mengalami erosi. Prinsip kebebasan dan kemandirian dalam menentukan sikap politik luar negeri, yang telah menjadi tulang punggung diplomasi Indonesia sejak era kemerdekaan, berpotensi bergeser menjadi sekadar “ikut-aktif” dalam agenda yang dirancang, dibiayai, dan diarahkan oleh kepentingan satu kekuatan besar.
Implikasi Kedaulatan dan Prinsip Bebas Aktif
Suherman lebih lanjut menguraikan bahwa meskipun amanat Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit mengamanatkan keterlibatan Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia, manifestasi dari peran tersebut seharusnya tidak mengarah pada pengikatan diri pada satu blok kekuatan dominan. Ia menekankan bahwa esensi dari perdamaian sejati terletak pada kemampuan sebuah negara untuk berdiri secara netral, mendapatkan kepercayaan dari semua pihak yang berkonflik, dan mampu menyuarakan pandangannya secara independen. Bergabung dalam sebuah forum yang didominasi oleh satu kekuatan besar seperti AS, menurutnya, bertentangan dengan filosofi netralitas dan kemandirian tersebut. Ia secara tegas menyatakan, “Saya pribadi tidak menolak peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Karena itu sudah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar, bahwa Indonesia terlibat dalam menjaga ketertiban dunia.” Namun, ia memberikan catatan penting mengenai bagaimana peran tersebut seharusnya diwujudkan, yaitu dengan tetap menjaga jarak dan kemandirian dari pengaruh dominan.
Kekhawatiran Suherman semakin menguat ketika menelisik rekam jejak Amerika Serikat dalam dinamika politik dan keamanan internasional. Sejarah menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri AS kerap kali diwarnai oleh kontroversi dan menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap stabilitas global. Dengan memasuki struktur yang secara inheren didominasi oleh Washington, Indonesia berisiko kehilangan independensinya dalam mengambil keputusan dan berpotensi terperangkap dalam pusaran kepentingan AS. Analisis Suherman ini secara implisit merujuk pada potensi Indonesia untuk kehilangan otonomi dalam merumuskan kebijakan luar negerinya sendiri, yang selama ini menjadi ciri khas diplomasi Indonesia.
Efektivitas Forum Internasional dan Potensi Menjadi Penonton
Lebih jauh, Suherman menyoroti efektivitas forum-forum internasional yang cenderung dikendalikan oleh negara-negara adidaya. Dengan merujuk pada pengalaman di sidang-sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di mana keputusan-keputusan strategis seringkali terbentur akibat penggunaan hak veto oleh negara-negara anggota tetap, ia mengkhawatirkan pola serupa akan terulang dalam Dewan Perdamaian yang baru ini. Jika skenario ini terjadi, Indonesia, meskipun menjadi anggota, dikhawatirkan hanya akan berperan sebagai penonton pasif atau “anak kemarin sore” yang turut serta dalam sebuah arena yang telah ditentukan oleh kepentingan negara lain, tanpa mampu memberikan dampak nyata atau mewujudkan tujuan perdamaian yang sesungguhnya. Ia menyimpulkan dengan tegas, “Imbasnya nanti kita hanya akan jadi penonton. Jadi, bermain ‘dewan-dewanan’ dengan AS rasanya adalah langkah yang keliru.” Pernyataan ini merupakan sebuah peringatan keras bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali arah kebijakan luar negeri agar tetap selaras dengan amanat konstitusi dan tidak terjebak dalam jebakan polarisasi kekuatan global yang dapat mengorbankan kedaulatan dan independensi bangsa.
Perlu dicatat bahwa daftar negara yang telah resmi bergabung dalam Dewan Perdamaian (BoP) hingga saat ini mencakup 22 negara, di antaranya adalah Amerika Serikat sebagai pemrakarsa, Israel, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Mesir, Yordania, Bahrain, Pakistan, Turki, Argentina, Vietnam, Kazakhstan, Mongolia, Uzbekistan, Azerbaijan, Armenia, Belarus, Maroko, Kosovo, dan Paraguay. Dengan bergabungnya Indonesia pada 22 Januari 2026, peta aliansi dan dinamika diplomasi global berpotensi mengalami pergeseran signifikan. Keputusan ini menuntut kajian mendalam mengenai hak dan kewajiban Indonesia sebagai anggota, serta jaminan prinsip kesetaraan dalam forum tersebut, sebagaimana yang dipertanyakan oleh berbagai pihak, termasuk akademisi seperti Dino Patti Djalal yang mengajukan setidaknya sembilan butir pertanyaan krusial kepada pihak terkait mengenai implikasi keanggotaan ini.